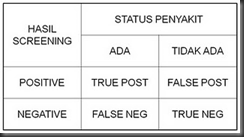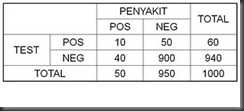A.PENGERTIAN, TUJUAN DAN KEGUNAAN
Kata epidemiologi berasal dari Bahasa Yunani, epi berarti pada/tentang, demos berarti penduduk, dan logos berarti ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk.
http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com
Epidemiologi adalah suatu metodologi ilmiah yang digunakan untuk mempelajari epidemi dan temuannya, dan hasil studi epidemiologi kemudian digunakan di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran untuk mengendalikan kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan mencegah terulangnya kejadian penyakit tersebut di masa mendatang.
Selain definisi asal kata, banyak definisi epidemiologi yang dibuat oleh ahli kesehatan. Definisi yang dibuat tersebut terkait dengan keadaan dan waktu, dikenal ada dua definisi yaitu:
1. Definisi lama (sebelum tahun 1960): Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan perluasan suatu penularan penyakit dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Dasarnya adalah sebelum tahun 1960 penyakit menular merupakan penyakit yang paling banyak dialami penduduk dunia.
2. Definisi baru (setelah tahun 1960): Beberapa tokoh yang terkenal dalam ilmu penyakit memberi definisi mengenai epidemiologi sebagai berikut.
a. Mag Mahon & Pugh (1970). Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit terhadap manusia.
b. Omran (1974). Epidemiologi adalah suatu studi mengenai kejadian dan distribusi kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk
c. Mausner & Kramer (1985). Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan penyakit dan kecelakaan pada populasi manusia.
d. Last (1988). Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasinya untuk menanggulangi masalah kesehatan.
e. “Epidemiologi adalah studi tentang faktor yang menentukan frekuensi dan distribusi penyakit pada populasi manusia”. (Lowe C.R. & Koestrzewski.J., 1973)
f. “Epidemiologi ialah suatu studi tentang distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia” (Barker, D.J.P., 1982)
g. “Epidemiologi ialah ilmu yang mempelajari distribusi penyakit atau keadaan fisiologis pada penduduk dan determinan yang mempengaruhi distribusi tersebut. (Lilienfeld A.M., & D.E. Lilienfeld, 1980)
Dari batasan tersebut terdapat persamaan yaitu semua menyatakan epidemiologi ialah ilmu yang mempelajari distribusi frekuensi penyakit heserta determinannya, hanya terdapat dua perbedaan yaitu tambahan fenomena fisiologis (Lilienfeld & Lilienfeld) dan ruda paksa (Mausner & Bhan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa epidemiologi ialah ilmu yang mempelajari penyakit, ruda paksa, dan fenotnena fisiologis tentang frekuensi distribusi dan determinannya pada kelompok manusia.
Epidemiologi dalam layanan kebidanan ialah epidemiologi yang mengkaji tentang distribusi dan determinan morniditas dan mortilitas dalam bidang kebidanan secara komperkensif. Artinya secara menyeluruh menyangkut seluruh sistem kebidanan termasuk kesehatan ibu dan anak (KIA).
Tujuan /kegunaan epidemiologi kebidanan ialah :
1.Untuk mengidentikasi penyebab penyakit dan faktor-faktor resiko terjadinya peyakit yang bisa menyerang ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas (42 hari setelah persalinan) serta pada bayi dalam kandunga hingga dilahirkan sampai asa balita.
2.Diharapkan akan didapatkan tekhnik pencegahannya.
Mengenai kegunaan epidemiologi secara umum yang sesuai dengan tujuan epidemiologi kebidanan dalam prakteknya sebagai berikut :
1.Menguraikan distribusi dan besarnya masalah suatu penyakit dalam masyarakat.
2.Memberikan data untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-proram pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit , serta untuk menentukan urutan prioritas program-program diatas.
3.Mengenal faktor-faktor penyebab penyakit (patogenesis).
4.Membantu pekerjaan administrasi kesehatan.
5.Untuk meneliti dan mengevalasi program pemberantasan penyakit dan masalah dalam kesehatan.
6.Untuk mendapatkan data dalam upaya mengklasifikasikan penyakit.
7.Untuk menyusun program pencegahan penyakit.
Kegunaan epidemiologi diatas dapat diringkas menjadi 3 hal, yakni :
1.Mendiskripsikan fenomena kesehatan masyarakat.
2.Mengkaji hubungan-hubungan sebab-akibat.
3.Melakukan evaluasi program kesehatan dan program intervensi.
Pada umumnya tujuan atau kegunaan epidemiologi kebidanan ialah untuk mengetahui faktor resiko pada ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, beserta hasil konsepsinya, dan mempelajari tekhnik-tekhnik pencegahannya termasuk evaluasi program kesehatan dan program intervensinya.
B.TERJADINYA PENYAKIT ATAU MASALAH KESEHATAN
1.Kaitan dengan Teori Segitiga Epidemi
Kaitan dengan teori terjadinya penyakit yang dicontohkan dalam segitiga Gordon, yakni hubungan antara agen, penjamu, dan lingkungan hidup, ketiganya harus berada dalam keseimbangan agar kondisi seseorang akan menjado sehat. Artinya bibit penyakit (agen) tidak berkembang biak dengan menginfeksi manusia bila kondisi bibit penyakit ditekan oleh lingkungan hidup yang sehat, penjamu dalam kondisi sehat jasmani dan sosial, sehingga daya tahan tubuh dalam kondisi optimal dapat menghalau terjadinya infeksi.
Pada KIA penjamunya adalah ibu, bayi, dan anak balita. Maka kondisi ibu, termasuk ibu hamil, bayi dan balita harus sehat jasmani rohani dan sosialnya. Hal itu bisa dicapai dengan pemenuhan gizi, dan berbagai perilaku sehat lainnya seperti olahraga, perilaku hidup bersih dan sehat, dll. Lingkungan hidup akan sangat berkaitan dengan lingkungan dalam rumah tangga secara fisik, biotik, sosial dan psikologis dari ibu, ayah, anak, tetangga, dan lainnya.
2.Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita
Angka kematian Ibu Indonesia 50/hari. Meski telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun hingga saat ini Angka Kematian Ibu (Maternal mortality Rate) di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara yakni 307/100.000 kelahiran hidup yang berarti 50 ibu meninggal setiap hari karena komplikasi persalinan dan saat melahirkan, itu menurut data tahun 2003. Namun pada tahun 2005 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 290,8/100.000 kelahiran hidup. Tapi kondisi itu tetap tidak merubah status indonesia sebagai negara dengan Angka kematian Ibu tertinggi di Asia Tenggara.
Menteri kesehata mengatakan guna menurunkan angka kematian ibu menjadi 226/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 Departemen Kesehatan telah menyiapkan 4 strategi pokok yakni penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Mendekatkan akses keluarga miskin da rentan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan surve dan pembiayaan dibidang kesehatan.
Terkait dengan pendanaan pemerintah mengalokasikan dana Rp 80 milyar untuk menukngkatkan kesehatan ibu dan anak.
USAID atau United States Agencynfor International Development memberikan bantuan untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia berupa bantuan dana dan pendampingan teknis dalam program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Health Services Program (HSP).
Direktur Bidang Kesehatan USAID Lynn Krueger Adrian mengatakan pada agustus 2004 bahwa pemerintah dan USAID menandatangani perjanjian kerjasama selama 5 tahun dibidang kesehetan. “Kami menyediakan dana sebesar 311 juta dolar AS untuk bidang kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak” katanya. Adrian menjelaskan sebagai langkah awal percontohan implementasi HSP melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak dari tingkat rumah sakit hingga puskesmas dilakukan di 30 kabupaten di 6 propinsi di Indonesia yakni Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Angka kematian ibu di ke 6 provinsi itu memang bukan yang terendah, kami memilihnya karena itu adalah provinsi terbesar di Indonesia yang dihuni oleh hampir 70 persen penduduk Indonesia sehingga akan ada signifikasi dalam penerapan program ini terhadap populasi,” ujar Adrian.
Berkenaan dengan hal itu,Menteri Kesehatan dan Adrian mengatakan bahwa pemerintah dan USAID secara berkala akan memantau pengaruh penerapan program ini terhadap penurunan angka kematian ibu,bayi dan anak.
“Tiap tahun akan dievaluasi dan dilihat melalui indicator yang jelas apakah program ini benar-benar bermanfaat,”katanya.
Keduanya mengatakan bahwa jika program itu berhasil dilakukan di 6 provinsi tersebut maka program itu selanjutnya akan dilakukan didaerah-daerah yang lainnya.
Selain yang tersebut diatas, the voice the Amerika memberitakan tentang Negara-negara miskin didunia sebagai berikut :
Laporan terkini dari LSM save the children menggambarkan gabungan potret usaha global untuk melindungi nyawa ibu dan anak balita (bawah 5 tahun), walaupun beberapa Negara di Afrika telah membuat banyak kemajuan dalam tahun-tahun terakhir, namun ternyata beberapa Negara Afrika lainnya berada hampir pada tingkat terbawah diantara 140 negara yang disurvey. Dari Washington, AS wartawan VOA William Eagle melaporkan.
Dibagian bawah indeks adalah Negara sub sahara yang tertinggi didunia dalam angaka kematian ibu dan bayi – Etiopia, Eritrea, Angola, guinea-bissau, chad, sierra leone, Yaman dan Djibouti. Nigeria adalah yang terakhir.
Untuk beberapa Negara, seperti Nigeria, Angola dan republic Demokratik kongo, angka yang tinggi juga mencermin kan jumlah penduduk mereka yang tinggi. Mereka bergabung degan 10 negara besar lain, termasuk china dan India, yang bila digabungkan mempunyai lebih dari separuh kematian ibu dan anak.
Perang juga bertanggung jawab terhadap angka kematian yang tinggi dinegara lain, termasuk sierra leonne, pantai gading dan Liberia.
Delapan puluh persen kematian anak balita di Afrika disebab kan oleh malaria, diare, pneumonia dan kelainan sejak lahir. Disebagian besar Negara di Afrika termasuk Botswana, Zimbabwe dan Swaziland, ternyata AIDS juga menjadi pembunuh utama pada anak balita dan inilah yang menjadi alasan utama mengapa Negara-negara ini belum mampu menurunkan angka kematian anak.
Diantara Negara-negara yang tingkat kematian ibu dan bayinya ditemukan lebih buruk dibandingkan 15 tahun yang lalu adalah Botswana, zimbabawe, dan Swaziland. Untuk Negara-negara ini, penyakit adalah faktor yang bermakna terhadap buruk nya tingkat hidup mereka.
Mieke Kiernan, direktur komunikasi save the children di Washington, AS berbicara tentang Zimbabwe.
“Angka kematian telah meningkat sebanyak 65 persen sejak 1990,” dia mengatakan” sebagian besar terkena HIV/AIDS. Kita mempunyai 1 diantara delapan anak yang meninggal sebelum mereka mencapai ulang tahunnya yang ke 5 dizimbabwe, lebih dari 40 persen dari kematian ini diakibat kan oleh AIDS. Zimbabwe, Afrika selatan, Botswana dan Swaziland adalah Negara dimana kita melihat HIV/ADIS melwebihi kemampuan prasarana untuk mendukung anak balita. Hal semacam ini sudah biasa diseluruh Afrika.
Kinerja ekonomi tidak selalu menunjukan layanan kesehatan terganggu oleh pandemi AIDS yang menyebar dibanyak tempat diAfrika bagian selatan.
Demikian halnya, angka kematian ibu dan bayi tetap tinggi dinegara penghasil minyak, termasuk Nigeria, Angola, dan guinea ekuatorial.
Tetapi Kiernan mengatakan bahwa keinginan politis akan berdampak besar terhadap Negara termiskin, termasuk Malawi. Dia mengatakan Malawi adalah cerita keberhasilan yang luar biasa dari Negara yang terbatas sumber daya nya, yaitu sebuah Negara yang sudah berfokus untuk ikut berperan didalamnya. Pendapatan perkapita (GNP) dimalawi kira-kira 650 dolar AS perorang, namun merekan telah melihat 43 persen penurunan angka kematian anak balita dalam 15 tahun terakhir ini.
Melawi telah mengambil beberapa langkah dia melanjutkan untuk menjadikan kesehatan ibu dan bayi sebagai prioritas utama mulai dari presiden sehingga jajaran dibawah. Mereka melakukan hal yang paling mendasar yang dapat ditiru oleh banyak Negara.
Diantara langkah yang mendasar ini adalah membagikan kelambu untuk melindungi ibu dan anak yang terinfeksi malaria, menyediakan perawatan kesehatan untuk ibu sebelum melahirkan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses pada suplemen gizi seperti vitamin A yang membantu menjaga melawan kekurangan gizi dan zink atau ZN serta oralit untuk menghentikan diare. Mereka juga dapat memastikan agar anak diimunisasi terhadap cacar dan penyakit- penyakit anak lainnya.
Kiernan mengatakan bahwa Tanzania adalah contoh Negara miskin lain yang sudah membuat banyak kemajuan melalui kekuatan politik:
“Tanzania adalah salah satu negara termiskin, dengan pendapatan 730 dolar AS per orang per tahun, namun mereka sudah mampu mengurangi angka kematian anak (balita) sebanyak 25 persen dan angka kematian bayi saat lahir sebanyak 20 persen dalam lima tahun terakhir,” dia mengatakan. “Kebanyakan dari kemajuan ini merupakan hasil dari peningkatan anggaran pemerinta untuk perawatan kesehatan ibu dan bayi” negara lain juga sudah memotong angka kematian anak sejak 1990.
Komitmen Madagascar untuk memperbaiki layanan kesehatan dan angka imunisasi membantu mengurangi angka kematian sebanyak 29 persen dan kekurangan gizi dari 42 persen menjadi 35 persen.
Di Etiopia, walaupun angka kematian ibu dan bayi masih tinggi namun telah mampu menurunkan angka ini secara menakjubkan yaitu 20 persen dalam 15 tahun terakhir.
Save the Children menemukan bahwa Mesir mengalami 63 persen penurunan kematian anak, dan keberhasilan ini sebagian karena adanya komitmen untuk membangun akses jalan di daerah perdesaan, dukungan strategi imunisasi, dan memastikan adanya bidan atau pekerja terlatih yang terampil untuk mendampingi kelahiran. Terkait hal ini Kiernan mengatakan tidak peduli seberapa besar keberhasilan yang terjadi di Mesir, namun terlihat bahwa selalu masih banyak yang perlu dilakukan untuk menurunkan kematian anak-anak.
3. Indikator Kesehatan Ibu Hamil dan Hasil Konsepsi
Indicator paling penting bagi kesehatan ibu hamil adalah angka kematian ibu (AKI/ maternal mortality rate/ MMR). Indicator paling penting terhadap hasil konsepsi pada masa kehamilan adalah angka kematian perinatal. Kematian ibu hamil atau kematian maternal adalah terjadinya kematian pada ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu hamil di suatu daerah tertentu selama 1 tahun dalam 100.000 kelahiran hidup.
Sedangkan mengenai kegunaan mengetahui informasi mengenai tingginya MMR/AKI adalah:
a.Untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi.
b.Untuk menyiapkan program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, dalam koridor KB atau keluarga berencana yang berpedoman untuk mencapai norma keluarga kecil bahagia sejahtera.
c.Untuk penyiapan system rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan.
d.Untuk melaksanakan persiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.
Kematian perinatal adalah terjadinya kematian saat dilahirkan atau disebut juga lahir mati serta kematian bayi selama minggu pertama kehidupan. Angka kematian perinatal adalah jumlah lahir mati dan bayi mati dalam minggu pertama dalam 1000 kelahiran hidup.
Berdasarkan hasil SDKI (survey demografi kesehatan Indonesia) 2002-2003 angka kematian ibu adalah 307/100.000 kelahiran hidup. Dalam SDKI tahun 1994 disebutkan bahwa angka kematian ibu adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian perinatal adalah 40 per 1000 kelahiran hidup. Sementara ada variasi yang terendah di Indonesia, yakni di Yogyakarta (130 per 100.000 kelahiran hidup) sedangkan tertinggi di Nusa Tenggara Barat (1340 per 100.000 kelahiran hidup).
Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian perinatal (AKP) yang masih tinggi itu telah lama mengundang perhatian pemerintah. Menurut hasil berbagai survey, AKI di Indonesia saat ini berkisar antara 300 dan 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKI di negara maju hanya sekitar 10 per 100.000 kelahiran hidup. AKI yang tinggi di Indonesia menunjukkan masih buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pemerintah sejak kemerdekaan melakukan berbagai kebijakan meliputi perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi baru lahir, seperti pelatihan dukun bayi, pengembangan klinik kesehatan ibu dan anak, pembangunan rumah sakit, pengembangan puskesmas, pengembangan pondok bersalin desa, dan pos pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu, pendidikan dan penempatan bidan di desa, dan penggerakan masyarakat untuk menyelamatkan ibu hamil dan bersalin, namun demikian hasil dari berbagai upaya tersebut diatas belum menggembirakan.
AKI yang masih tinggi dengan penurunan lambat merupakan fenomena di banyak negara berkembang. Situasi yang memperihatinkan ini mendorong kelahiran IMMPACT yang merupakan akronim dari initiative for mortality programme assessment. IMMPACT merupakan suatu inisiatif riset global dengan tujuan menemukan strategi penurunan kematian ibu yang cocok dalam arti efektif dan kos-efektif berdasarkan bukti dengan konteks social budaya di banyak negara berkembang, dan menilai kelayakan strategi dalam mendorong pemerataan dan kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
Sejauh ini program IMMPACT telah dilakukan di tiga negara, yaitu: Ghana dan Burkina Faso di Afrika, dan Indonesia. Di Indonesia program IMMPACT dilakukan di dua kabupaten yaitu di Provinsi Banten, yaitu di Kabupaten Serang dan Kabupaten Padeglang. Penetapan kedua lokasi ini dilakukan setelah dilakukan studi banding di 8 lokasi potensial meliputi Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang. Pemilihan lokasi dilakukan atas pertimbangan, antara lain : variasi aspek yang terkait dengan kesehatan ibu (geografis, pelayanan kesehatan, dan sosio demografi), keberadaan program penyelamatan ibu dengan strategi making pregnancy safer (MPS) dan program terkait lain, angka kematian dan keehatan yang belum optimal, kepemimpinan dan komitmen kabupaten, akses dengan institusi penelitian, dan ketersediaan data.
Strategi program IMMPACT dimulai dengan pengembangan instrument sebagai alat evaluasi strategi upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, mengidentifikasi upaya yang layak evaluasi, penelitian evaluasi dan pada akhirnya penemuan strategi yang efektif dan kos-efektif dengan konteks social budaya Indonesia. Program IMMPACT direncanakan akan berjalan selama 7 tahun. Sejak pencanangan bulan mei 2003, IMMPACT telah merancang dan menguji-cobakan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan untuk evaluasi strategi upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) dan di masyarakat.
Dalam menyambut Hari Kesehatan Dunia 2005 yang bertemakan ‘IBU SEHAT, ANAK SEHAT SETIAP SAAT’, bekerja sama dengan sector kesehatan Kabupaten Serang, IMMPACT menyelenggarakan seminar sehari pada tanggal 12 April 2005 untuk menyampaikan beberapa hasil kegiatan IMMPAC. Seminar berlangsung di aula Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dengan jumlah peserta 83 orang yang mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Banten, semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Banten, semua puskesmas kecamatan dan rumah sakit di Kabupaten Serang dan Kabupaten Padeglang, Kantor Statistik Kabupaten Serang dan Kabupaten Padeglang, dan berbagai organisasi kemasyarakatan terkait. Seminar sehari ini membahas tiga topic penyajian : (1) Mengukur angka kematian ibu melalui survey di rumah sakit dan puskesmas, (2) Faktor penghambat dan pemudah pencatatan laporan kematian ibu oleh masyarakat, dan (3) nyaris mati dan unmeet obstetric need sebagai indicator pelengkap program penyelamatan ibu.
Dalam mengenalkan program IMMPACT, Prof. dr. Budi Utomo, MPH, Ph. D menyampaikan beberapa isu yang menyangkut upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. Salah satu isu yang penting adalah mulai tumbuhnya kesadaran perlunya penggunaan data dalam pengembangan kebijakan, tetapi dalam banyak hal penggunaan data belum mmbudaya di lingkungan manajer kesehatan. Banyak data dikumpulkan, tetapi sebagian besar tidak digunakan secara rutin. Lebih dari itu, data yang dibutuhkan sering kurang tersedia. Isu penting lain yang disampaikan adalah kecenderungan mengadopsi strategi yang mungkin efektif di negara lain tanpa kajian kritis, yaitu menilai kesesuaian strategi tersebut dengan konteks Indonesia. Padahal kajian kritis ini diperlukan untuk menghindari penghamburan sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini IMMPACT berupaya membantu mitra untuk pengambilan kebijakan.
Sementara AKI diperlukan untuk menilai keberhasilan upaya penyelamatan ibu, pengukuran AKI di Indonesia bukan perkara mudah karena system pencatatan kelahiran dan kematian belum berjalan dengan baik. Sampai saat ini AKI di Indonesia diperkirakan tidak langsung dari data kelangsungan hidup saudara perempuan yang diperoleh melalui survey rumah tangga. Dalam survey ini semua perempuan usia reproduksi di rumah tangga yang masuk survey dinyatakan mengenai status hidup saudara-saudara perempuan mereka. Selanjutnya apabila sudah meninggal, dinyatakan apakah meninggalnya saat hamil, bersalin, atau nifas. Cara ini mahal karena memerlukan sampel rumah tangga yang tersebar di masyarakat. Dalam konteks ini, dr. Nurul Qomariah M. Kes menyajian upaya IMMPACT untuk mencari metode pengukuran AKI yang lebih murah dan lebih praktis disbanding metode pengukuran yang sekarang ini dilakukan.
Untuk mendapatkan data kelangsungan hidup saudara perempuan dari semua perempuan usia reproduksi, IMMPACT melalui dr. Nurul mengajukan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit danpuskesmas sebagai satu alternative tempat pengambilan sampel. Dengan pendekatan ini, petugas pengumpul data tidak harus mengunjungi semua sampel rumah tangga yang letaknya sangat tersebar di masyarakat. Sebagai uji-coba, IMMPACT menggunakan rumah sakit daerah dan lima puskesmas terpilih di Kabupaten Serang dan Kabupaten Padeglang sebagai tempat pengambilan sample perempuan usia reproduksi. Sebagai responden adalah perempuan usia reproduksi pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan bukan pasien rawat inap. Uji coba pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan (19 juli-agustus 2004) dengan jumlah responden 2.985 perempuan.
Hasil uji-coba menunjukan bahwa dari variable social ekonomi yang terkait dengan Angka Kematian Ibu, pengunjung rumah sakit dan pengunjung puskesmas Serang Kota cenderung berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat social-ekonomi yang lebih tinggi dibanding masyarakat kebanyakan di Provinsi Banten. Namun demikian, pengunjung perempuan usia reproduksi di empat puskesmas yang lain ternyata dari tingkat social ekonomi sebanding dengan masyarakat kebanyakan di provinsi banten. Hasi uji coba menyimpulkan bahwa puskesmas-puskesmas di kabupaten Serang dan Kabupaten Padeglang amat potensial sebagai tempat pengambilan sampel survey perempuan usia reproduksi untuk mendapatkan data kelangsungan hidup saudara perempuan, tidak saja pengunjung yang mewakili masyarakat kebanyakan, tetapi juga jumlah pengunjung yang relatif banyak dan rendahnya angka penolakan pengunjung untuk berpartisipasi dalam survei.
Fokus penelitian IMMPACT bukan hanya di fasilitas kesehatan melainkan juga di masyarakat. Untuk mendapatkan mekanisme pelaporan dan pencacatan kematian yang lebih baik, IMMPACT melalui Dra. Evi Martha, M.kes. melaporkan hasil penelitian kualitatif tentang faktor penghambat dan pemudah pelaporan kem,atian oleh masyarakat di Desa Sentul,kecamatan kragilan, kabupaten serang dan desa bulagor,kecamatan pagelaran, kabupaten pandeglang hasil penilitian menunjukan bahwa selama ini anggota masyarakat umumnya sudah melaporkan kematian yang terjadi dikeluarganya,namun tidak konsisten kepada siapa dengan cara bagaimana kematian tersebut dilaporkan. Pihak yang menerima laporan kematian bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari penjaga mesjid, kader, bidan, kedua RT, dukun bayi, dan tokoh masyarakat sampai ke desa. Mereka yang menerima laporan kewmatian ini ternyata tidak melaukan pencacatan tertulis secara sistematis.alasan mendapat bantuan, diumumkan ke anggota masyarakat yang lain dan untuk mendapatkan surat keterangan. Sebagian besar masyrakat ternyata melaporkan kematian ke mesjid. Ketidaktahuan dan kekurangan pedulian masyrakat dan petugas merupakan penghambat. Sedangkan kebiasaan melapor kematian merupakan peluang untuk melaporkan kematian oleh masyrakat.
IMMPACT melaui dr. Asri Adisassmita, MPH, ph.D menyajikan kemungkinan data nyaris mati dan kebutuhan obstetrik yang tidak terpenuhi untuk penyelamata n ibu situasi gawat obstetrik dan tindakan besar obstetrik merupakan peristiwa-peristiwa yang dekat dengan kematian ibu .ibu nyaris mati diartikan sebagai ibu dengan komplikasi obstetrik yang mengancam jiwa yang berhasil hidup karena faktor kebetulan atau karena perawatan yang baik.dari frekuensi kejadian.jumlah nyaris mati lebih banyak dibanding dengan kematian sehingga nyaris mati berpotensi digunakan sebagai indikator. Namun masalah yang masih dihadapi adalah pengembangan kriteria yang cocok untuk menentukan apakah seseorang ibu dengan komplikasi obstetrik yang bagaimana layak untuk dimasukkan dalam kategori nyaris mati.dalam konteks yang setempat, kriteria nyaris mati sementara ini dikembangkan melalui data yang ada dan diskusi panel ahli dalam rumah sakit yang bersangkutan.
Sedangkan konsep unmeet obstetric need merujuk kepada satu situasi komplikasi obstetrik tetapi tidak mendapatkan pelayanan tindakan besar obstetrick.jadi unmeet obstetric need menunjukan suatu kesenjangan antara kebutuhan tindakan pelayanan di satu pihak dan tindakan pelayanan di pihak yang lain.
Salah satu upaya menangani kematian ibu hamil, departemen kesehatan republik indonesia bekerjasama dengan WHO, UNICEF, dan UNDP. Sejak tahun 1990-1991 melaksanakna kegiatan yang dikenal sebagai program safemotherhood. Dalam kegiatan tersebit dilakukan intervensi yang disebut 4 pilar safemotherhood:
1.Keluarga berencana
2.Pelayanan antenatal
3.Persalinan yang aman
4.Pelayanana kebidanan esensial
C.FAKTOR RESIKO TERJADINYA MASALAH KESEHATAN
Faktor-faktor resiko untuk ibu hamil diklasifikasi:
1.Faktor-faktor reproduksi
a.Usia
b.Paritas
c.Kehamilan yang tak diinginkan
2.Faktor-faktor akibat komplikasi kehamilan
a.Perdarahan pada abortus spontan
b.Kehamilan ektopik
c.Perdarahan pada trimester 3 kehamilan
d.Perdarahan postpartum
e.Infeksi pada saat nifas
f.Gestosis
g.Distosia
h.Abortus propokatus
3. Faktor-faktor pelayanan kesehatan
a.Kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan maternal
b.Asuhan medis yang kurang baik
c.Kekurangan tenaga terlatih dan obat-obatan esensial
4.Faktor-faktor sosial budaya
a.Kemisikinan sehinnga tidak mampu membayar pelayanan yang baik
b.Ketidaktahuan
c.Kesuliatan transportasi
d.Status wanita yang rendah dan mersa rendah diri
e.Pantang makan tertentu saat hamil
Faktor-faktor resiko untuk balita adalah:
1.Peranan nutrisi yang kurang sehat karena :
a.Kemisikinan
b.Ketidak tahuan
2.Perilaku tidak sehat misalnya:
a.Tempat dan bahan permainan yang kotor dan berbahaya contoh:
1)Mandi di sungai yang kotor
2)Bermain diatas tanah tanpa alas kaki serta bermain tanah kotor atau bermain ditempat yang kotor
3)bahan permainan yang tajam atau berbahaya, miisalnya permainan kendaraan, kapal mainan, dan lain-lain secara tradisional dengan bahan yang tajam
4)bermain tanpa memperhatikan waktu dan kondisi udara yang panas terik.
5)membeli makanan dan kue dijalanan yang tidak higinis dan mengandung bahan berbahaya dan beracun, (B-3)seperti dawet dan air mentah, minuman dengan pewarna yang mengandung bahan berbahaya dan lain-lain
b.Membersihkan gigi tidak memperdulikan waktu dan cara bersikat gigi yang benar.
Referensi
1. Noor, 1997, Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular, Jakarta, PT. Rineka Cipta
2. Bustan, 2000, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Jakarta, PT. Rineka Cipta
3. Bustan, 2002, Pengantar Epidemiologi, Jakarta, PT. Rineka Cipta
4. Notoatmojo, 2003, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip Prinsip Dasar, Jakarta, PT. Rineka Cipta
5. Entjang, 2000, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
6. Vaughan, Morrow, 1993, Panduan Epidemiologi Bagi Pengelolaan Kesehatan Kabupaten, Bandung, ITB
http://mulkasem.blogspot.com/
http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com